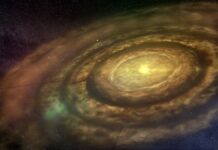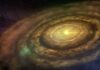Perubahan iklim bukan lagi sebuah ancaman; dampaknya kini semakin besar, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai masa depan migrasi manusia. Dalam bukunya “Sink or Swim,” pakar adaptasi iklim Susannah Fisher memaparkan skenario buruk pada tahun 2070, dimana kenaikan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan kelangkaan sumber daya mendorong perpindahan massal. Ini bukan sekadar proyeksi; mereka mengeksplorasi pilihan-pilihan nyata yang dihadapi umat manusia, menyoroti pentingnya perencanaan sekarang demi masa depan yang dibentuk kembali oleh perubahan iklim.
Dua Dunia Muncul:
Bayangkan dua realitas yang kontras. Salah satunya adalah perbatasan yang diperketat seiring menyusutnya wilayah yang tidak dapat dihuni. Negara-negara yang menghadapi kekurangan air memasang penghalang, sehingga mereka yang kehilangan tempat tinggal hanya mempunyai pilihan yang terbatas. Bantuan kemanusiaan kesulitan mengimbangi laju pengungsi, hanya menawarkan bantuan sementara namun gagal mengatasi penyebab mendasar dari pengungsian. Kesenjangan global pun muncul – yaitu zona layak huni yang dihuni oleh mereka yang cukup beruntung untuk tinggal di wilayah yang berketahanan dan zona “non-hab” yang mencakup wilayah-wilayah terpencil yang bergulat dengan kerusakan iklim. Keputusasaan melahirkan solusi yang tidak lazim: komunitas yang terpecah belah bereksperimen dengan geoengineering dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan tanah mereka.
Skenario kedua menawarkan secercah harapan di tengah tantangan yang ada. Di dunia ini, perjanjian internasional yang terkoordinasi memungkinkan migrasi terkelola yang dipicu oleh bencana iklim. Negara-negara mengakui tanggung jawab atas emisi historis dan menawarkan jalan untuk relokasi – sebuah jalur penyelamat yang diperluas oleh negara-negara seperti negara-negara yang pernah memicu pemanasan global. Setiap individu menerima “paspor iklim”, yang memungkinkan mereka memilih tujuan berdasarkan faktor-faktor seperti peluang dan ikatan keluarga.
Perusahaan bahan bakar fosil dimintai pertanggungjawaban melalui kasus-kasus hukum yang penting, dengan berkontribusi pada dana relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak. Bangladesh, yang dilanda topan, menerima fasilitas pengungsian dari PBB, sehingga memungkinkan keluarga untuk menetap di kota-kota sekunder yang menawarkan stabilitas dan peluang untuk pendidikan dan karir baru.
Menemukan Kesamaan:
Komunitas Norfolk yang tercerabut akibat erosi pantai mendapatkan hiburan tidak hanya melalui program relokasi yang telah ditentukan namun juga melalui lembaga – mereka melakukan transisi dengan dukungan pemerintah, memastikan kesinambungan budaya dan ikatan dengan tempat asal mereka. Sementara itu, negara kepulauan menerapkan strategi adaptasi seperti anjungan terapung dan reklamasi lahan, sekaligus menawarkan dukungan bagi mereka yang memilih untuk bermigrasi. Mereka membentuk apa yang disebut Fisher sebagai “negara jaringan,” yang berakar pada ketahanan namun saling terhubung di berbagai lokasi, memadukan tradisi dengan realitas perubahan yang disebabkan oleh iklim.
Narasi masa depan ini bukan sekadar spekulasi; mereka menyoroti pilihan besar yang harus diambil umat manusia dalam menghadapi dampak iklim yang semakin meningkat. Mereka mendesak kita untuk mempertimbangkan tidak hanya solusi global tetapi juga bagaimana individu, komunitas, dan negara menavigasi transisi yang rumit ini.
Jalan ke depan memerlukan diskusi yang sulit, peralihan dari respons bencana yang reaktif ke strategi adaptasi yang proaktif, dan pengakuan bahwa keadilan iklim menuntut beban dan manfaat yang adil. Jam terus berdetak. Mengabaikan kenyataan yang nyata, Fisher menghadirkan risiko tenggelam ke dalam masa depan yang lebih kacau dan tidak adil – sehingga kita hanya mempunyai pilihan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pilihan yang dieksplorasi dalam skenario menariknya.